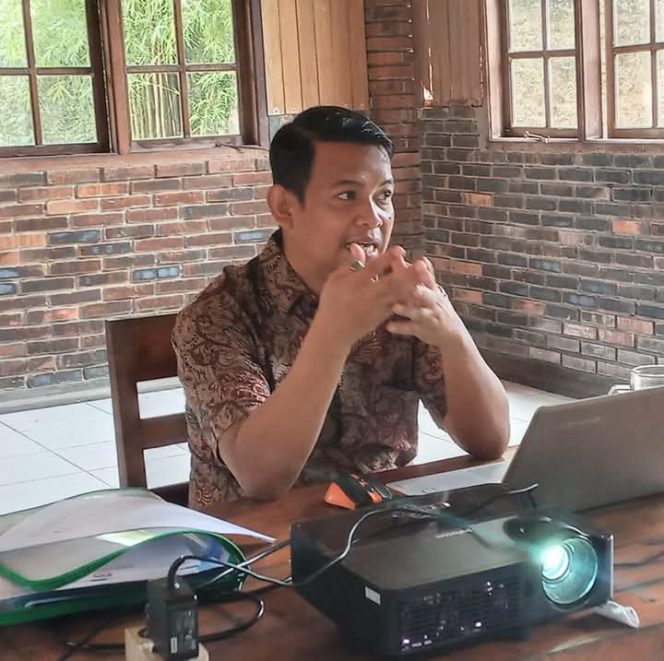NUSAKATA.COM – THR | Jelang lebaran selalu punya cara menciptakan aroma khas. Bukan hanya dari dapur yang penuh wangi opor ayam, atau jalanan yang riuh pemudik. Namun, juga dari percakapan-percakapan hangat.
Salah satunya soal Tunjangan Hari Raya (THR). Selalu jadi perbincangan tahunan. Bahkan, tak jarang jadi polemik. Entah sebagai hak yang wajib diberikan, atau ironisnya, jadi objek permintaan tak pada tempatnya.
Mari kulik lebih dalam. Tak sekadar soal uang tambahan menjelang lebaran, THR ternyata punya sejarah panjang yang menarik.
THR bukan barang baru. Tradisinya berakar pada masa pemerintahan Orde Lama. Tahun 1954, kala itu Indonesia masih mencari bentuk ekonomi yang stabil. Pemerintah melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengeluarkan kebijakan memberi tunjangan kepada para pegawai negeri menjelang Idulfitri.
Kebijakannya lahir dari situasi sosial. Kala itu, banyak buruh dan pegawai mengeluhkan kondisi keuangan yang seret. Di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung.
Pemerintah mencoba menjawab keresahan tersebut dengan memberikan semacam “uang kadeudeuh”. Atau uang kasih sayang. Agar pegawai bisa merayakan Lebaran dengan layak.
Lama-lama, kebiasaan ini mengeras menjadi aturan. Terutama saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Mewajibkan pemberian THR kepada pekerja swasta minimal satu kali gaji pokok. Tak lupa, bagi pegawai negeri, besaran dan waktu pencairannya pun diatur ketat lewat Peraturan Pemerintah.
Dari situ, THR berubah menjadi hak normatif pekerja. Tak lagi sekadar hadiah, melainkan bagian dari penghargaan atas kerja keras setahun penuh.
Namun, di balik semangat penghargaan itu, ada fenomena lain yang berkembang. Kita mungkin familiar dengan surat-surat permohonan THR yang beredar ke meja instansi atau kantor-kantor swasta.
Datang dari berbagai pihak. Mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media, hingga, ironisnya, di lingkup instansi pemerintahan sendiri.
Ada surat resmi berkop lembaga, meminta THR untuk keperluan operasional. Ada pula yang mengatasnamakan komunitas, bahkan individu. Alasan mereka beragam. Dari membantu kegiatan sosial, hingga sekadar menjaga hubungan baik.
Fenomena ini sebenarnya sudah cukup lama. Namun, di era digital seperti sekarang, mudah sekali kita menemukan contoh permohonan THR beredar di media sosial, kadang disertai kontroversi.
Pertanyaannya, kenapa budaya meminta THR di luar hubungan kerja formal ini bisa marak?
Satu jawabannya bisa kita temukan ialah kultur patronase yang masih lekat di masyarakat kita. Hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang membantu seringkali tak lepas dari praktik timbal-balik.
Dalam dunia jurnalistik, misalnya. Ada beberapa oknum wartawan yang terbiasa menyodorkan proposal THR ke narasumber, terutama yang berasal dari instansi atau perusahaan. Tak jarang, bahasa yang digunakan bersifat halus tapi menyiratkan kewajiban moral untuk memberi.
Hal serupa juga terjadi di lingkup LSM atau ormas. Mereka kerap mengajukan permohonan THR kepada pejabat daerah atau pengusaha lokal, atas nama menjaga sinergi atau mendukung program sosial.
Di lingkup dinas, fenomenanya kadang lebih absurd. Antar institusi pemerintah saling mengajukan permohonan bantuan THR, seolah lupa bahwa mereka bekerja di bawah satu atap negara yang sama.
Masalahnya, praktik semacam ini rentan melenceng. Dari sekadar tradisi pemberian sukarela, berubah menjadi beban yang terkesan memaksa. Tak jarang pula menyerempet area abu-abu etika, bahkan hukum.
Banyak pihak mulai angkat suara. Saya menilai, praktik permohonan THR di luar konteks hubungan kerja sebagai bentuk mentalitas yang tidak sehat. Bukannya menguatkan profesionalisme, malah membuka ruang transaksional yang tak perlu.
Beberapa organisasi pers pun sudah memberikan arahan tegas. Dewan Pers, misalnya, mengingatkan wartawan untuk menjaga independensi dan tidak menyalahgunakan profesi dengan meminta THR atau amplop kepada narasumber.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Budaya ini seperti sulit dicabut akar-akarnya. Bagi sebagian orang, meminta THR dianggap wajar. Bahkan jadi bagian dari hak tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun.
THR seharusnya tetap pada relnya. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tenaga dan pikiran, bukan sekadar tradisi minta-minta. Dunia kerja modern menuntut profesionalisme yang bersih dari praktik transaksional di luar ketentuan.
Bagi para pengelola lembaga, baik itu media, LSM, maupun dinas pemerintahan, perlu ada refleksi mendalam. Apakah proposal permohonan THR benar-benar masih relevan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas hari ini?
Bukankah lebih elegan jika hubungan kelembagaan dibangun lewat kinerja dan kontribusi nyata, bukan permintaan musiman yang berpotensi menimbulkan rasa sungkan atau beban bagi pihak lain?
Lebaran merupakan tentang kembali pada kesucian. Membersihkan hati dari dendam, kesalahan, dan, tentu saja, dari praktik-praktik yang membebani sesama.
Mari kembalikan makna THR pada tempatnya. Sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan. Bukan ajang proposal atau formalitas sosial yang menguras martabat.
Karena pada akhirnya, yang paling indah dari Lebaran bukanlah amplop berisi uang. Melainkan tangan yang terbuka tanpa syarat, yang memberi tanpa diminta, dan menerima tanpa memaksa.
Ditulis oleh: Subandi Musbah. Direktur Visi Nusantara.