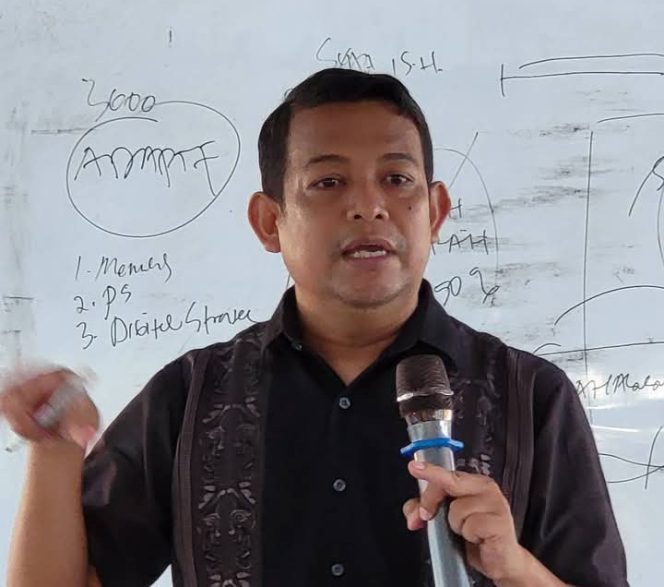KAMPUS | Jika ilmu harus bermanfaat bagi masyarakat, lalu sejauh mana kampus mampu menerjemahkan semangat Tri Dharma ke dalam tindakan nyata?
Mari kita telusuri dari awal. Bukan untuk menyalahkan masa kini, tapi sekadar memahami ke mana seharusnya langkah ini dibawa. Semacam pandangan atau cara membaca penomena yang sedang terjadi.
Tri Dharma lahir bukan sekadar rumusan administratif. Ia merupakan filsafat pendidikan yang sudah ditanamkan dalam norma. Sejak lama. Sekira 60 tahun silam. Era akhir kepemimpinan Sukarno.
Kala itu, negara sedang proses pembangunan. Dan perguruan tinggi menjadi salah satu sumbu peradaban. Bukan pabrik ijazah, tapi tempat menyalakan obor pengetahuan dan keberpihakan sosial.
Filosofi di baliknya begitu sederhana, tapi mendalam. Bahwa ilmu tak boleh berhenti di kepala. Bahwa kampus tak boleh hanya jadi menara gading. Ilmu harus hidup, tumbuh, dan berguna bagi sesama.
Tri Dharma merupakan jalan agar akademisi tak kehilangan arah. Bahwa jadi cendekia bukan sekadar soal pintar, tapi soal tanggung jawab. Juga soal bagaimana membumikan ilmu pengetahuan.
Mari kita mulai dari yang pertama: pendidikan dan pengajaran.
Ini fondasi utama. Mahasiswa datang bukan hanya untuk dapat gelar. Mereka datang mencari makna. Menemukan jalan. Di sinilah peran dosen menjadi sentral. Bukan sekadar pengisi kelas, tapi penuntun kehidupan.
Pengajaran bukan hanya soal kurikulum, tapi soal inspirasi. Soal bagaimana membentuk karakter. Membuka cakrawala. Menumbuhkan kedewasaan. Merangsang berpikir. Sampai mengasah ketajaman dialektika.
Sayangnya, dalam praktik, sering kali pembelajaran jadi kaku. Berorientasi nilai. Penuh tugas. Jauh dari ruang dialog. Padahal Paulo Freire pernah bilang, pendidikan itu harus membebaskan, bukan menindas.
Berlanjut ke penelitian dan pengembangan.
Ini merupakan napas kampus. Tempat ide bertemu metodologi. Tempat keresahan menjadi karya. Dosen dan mahasiswa seharusnya menjadi penjelajah pengetahuan. Selalu menemukan hal-hal baru.
Namun, sayangnya riset di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Minim dana. Banyak syarat administratif. Dan kadang kehilangan arah: hanya sekadar memenuhi kewajiban akreditasi. Tidak lebih.
Padahal riset seharusnya menyentuh kehidupan. Menjawab persoalan sosial. Menemukan teknologi tepat guna. Menghadirkan inovasi. Bukan sekadar menumpuk jurnal. Apalagi yang tak pernah dibaca.
Ketiga, pengabdian kepada masyarakat.
Ini dharma yang paling manusiawi. Ilmu yang disemaikan di kampus, harus kembali ke rakyat. Lewat program pemberdayaan, pelatihan, atau sekadar menjadi telinga bagi keresahan masyarakat.
Pengabdian bukan formalitas. Bukan pula safari akademik. Melainkan kolaborasi. Belajar bersama. Tumbuh bersama. Saling berbagi. Saling memberi. Untuk kesejahteraan bersama.
Sayangnya, sebagian kampus menjadikan pengabdian sekadar formalitas. KKM (Kuliah Kerja Masyarakat) dilakukan hanya satu bulan. Itu pun setiap hari Sabtu dan Minggu.
Dilaksanakan hanya untuk melengkapi laporan. Padahal sejatinya, pengabdian merupakan denyut sosial dari intelektual. Masyarakat bukan objek, tapi subjek. Mereka bukan “dibantu”, tapi “disapa”.
Di kampus-kampus negeri, program KKM merupakan contoh bagaimana pengabdian bisa jadi gerakan sosial. Mahasiswa hidup di desa. Bekerja bersama warga. Dan pulang membawa cerita, bukan hanya lembar laporan.
Lalu, apakah Tri Dharma masih relevan hari ini? Kita hidup di era digital. Segalanya serba cepat. Serba instan. Ilmu berserakan di mana-mana. Kampus tak lagi satu-satunya sumber belajar. YouTube, podcast, dan kursus daring menjamur. Bahkan AI bisa menjawab soal lebih cepat dari dosen.
Namun, justru di sinilah letak tantangannya. Di tengah banjir informasi, peran kampus bukan lagi penyampai pengetahuan, tapi penyaring kebijaksanaan. Bukan tempat menghafal, tapi tempat memaknai. Tri Dharma bisa menjadi kompas. Menjaga arah agar kampus tak kehilangan jiwanya.
Pendidikan harus bertransformasi. Menyentuh digital, tapi tetap humanis. Pengajaran bisa hybrid, tapi jangan hilangkan interaksi. Mahasiswa boleh diajar dari layar, tapi harus tetap disentuh dengan cerita.
Penelitian pun harus adaptif. Gunakan big data. Manfaatkan teknologi, tapi jangan lupakan etika. Riset tetap harus jujur. Bukan sekadar memenuhi algoritma. Tidak boleh lagi ada riser bayaran. Apalagi manipulasi kesimpulan.
Transformasi digital seharusnya tak menenggelamkan Tri Dharma. Justru bisa menguatkan. Dengan syarat: nilai dasarnya jangan dilupakan. Bahwa ilmu bukan milik segelintir. Pendidikan harus membebaskan. Dan masyarakat bukan beban, tapi kawan seperjalanan.
Memang, tantangan tak ringan. Banyak kampus tergoda jadi korporasi. Uang jadi panglima. Mahasiswa jadi klien. Ilmu dikomersialkan. Dosen diburu administrasi. Bahkan jual-beli ijazah kerap terjadi.
Namun, harapan itu belum hilang. Masih banyak dosen yang tulus. Mahasiswa yang resah tapi tetap belajar. Kampus yang terus berinovasi, tanpa melupakan jati dirinya.
Seperti kata Ki Hajar Dewantara:
“Ing Ngarsa Aung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.” Di depan memberi teladan. Di tengah membangun semangat. Di belakang memberi dorongan. Tri Dharma merupakan bentuk konkret dari semboyan itu.
Akhirnya, pertanyaan di awal tadi masih relevan: Apakah perguruan tinggi masih bisa jadi lokomotif kemajuan? Jawabannya ada pada kita semua. Pada dosen yang tetap menyalakan api. Pada mahasiswa yang terus bertanya. Pada kampus yang tetap menjaga nurani.
Karena sejatinya, ilmu tanpa pengabdian hanyalah kesombongan. Dan kampus tanpa keberpihakan hanyalah bangunan kosong. Semoga, ketika anak-anak kita kelak bertanya apa arti kampus, kita bisa menjawab dengan tenang: tempat belajar hidup, bukan sekadar tempat mengejar nilai.
Oleh : Subandi Musbah